Kiamat Media Sosial: Saat Remaja Australia Dipaksa Offline, Indonesia Masih Terjebak Scroll Tak Berujung
- Dok Freepick
Penulis: Budi Yuniharto, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina
Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Di sebuah kota kecil di pinggiran Sydney, Emma Mason duduk di meja dapur yang sama tempat ia menerima panggilan terburuk dalam hidupnya tiga tahun lalu.
Telepon itu membawa kabar bahwa putrinya, Tilly, seorang gadis remaja berusia 14 tahun mengakhiri hidupnya setelah di-bully habis-habisan di Instagram.
Kini, pada Desember 2025, Emma menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk.
Undang-undang baru Australia yang mulai berlaku 10 Desember 2025 ini—tentang larangan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun—adalah buah kampanyenya yang gigih.
"Ini bukan akhir dunia, tapi awal dari dunia yang lebih aman bagi mereka,” katanya dalam wawancara dengan Sky News dikutip Senin (8/12/2025).
Bagi remaja Australia, peraturan ini terasa seperti kiamat. Dunia maya yang selama ini menjadi ruangnya tiba-tiba direnggut.
TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube—semua platform itu akan memblokir akun remaja di bawah umur.
Meta bahkan sudah mulai menutup akun anak-anak sejak minggu lalu, sementara YouTube menjanjikan akses kembali saat ulang tahun ke-16.
Pemerintah Australia menyebut langkah ini sebagai "eksperimen nasional terbesar" untuk melindungi kesehatan mental generasi muda di tengah data yang mengerikan, yakni lebih dari 40% remaja Australia (pada gadis usia 15-19 tahun) mengalami distress mental dengan lonjakan 70% rawat inap akibat self-harm sejak 2008.
Cyberbullying, perbandingan sosial, dan kecanduan algoritma menjadi musuh utamanya.
Seorang remaja bernama Sarah (15) membagikan pandangannya di X tentang “kiamat media sosial” ini.
"Media sosial adalah tempatku bicara dengan teman-teman yang paham perjuanganku. Tanpa itu, aku merasa sendirian”.
Fenomena ini bukan sekadar kebijakan teknologi, melainkan panggilan mendesak bagi manajemen media baru atau new media—yang selama ini dianggap sebagai jembatan koneksi kini terbukti sebagai jurang isolasi.
Di Australia, larangan ini lahir dari krisis nyata. Studi tahun 2023 menunjukkan screentime berlebih mengganggu perkembangan kognitif.
Anak-anak menghabiskan 40% lebih banyak waktu di platform sosial yang berkontribusi pada penurunan prestasi akademik dan interaksi sosial.
Emma bukanlah satu-satunya yang menyalurkan suara. Ribuan orang tua bergabung dalam sebuah petisi didukung data dari eSafety Commissioner yang mencatat 20% remaja Australia mengalami cyberbullying.
Kritikus menyebut ini terlalu ekstrem: Bagaimana dengan hak privasi dan kebebasan berekspresi?
Namun, bagi pemerintah setempat, manfaatnya jelas.
Sementara itu, di Indonesia—negara dengan 170 juta pengguna media sosial tertinggi keempat di dunia—masih bergulat dengan "kiamat" yang sama, tapi tanpa rem yang sekuat Australia.
Rina, seorang siswi SMA di Jakarta, setiap malam scroll salah satu platform media sosial hingga larut.
Dia mengaku membandingkan kulitnya yang "kurang glowing" dengan influencer berwajah sempurna.
"Aku merasa jelek terus," ceritanya dalam survei Mum.id tahun 2025 di mana 96,4% remaja Gen Z mengaku kesulitan mengatasi stres dari media sosial.
Di sini dampaknya tak lagi abstrak. Penggunaan media sosial naik 200% sejak pra-pandemi dan tren ini diprediksi bertahan hingga 2025.
Ini membuat aktivitas luar ruangan remaja turun drastis setelah melebihi dua jam sehari.
Indonesia bukan asing dengan badai new media. Salah satu platform media sosial disebut-sebut menjadi sumber utama paparan konten negatif: body shaming, kekerasan digital, dan tantangan berbahaya yang mendorong kenakalan remaja.
Penelitian Universitas Airlangga tahun 2025 menyoroti bagaimana algoritma platform tersebut memperburuk kesehatan mental dengan remaja terpapar standar kecantikan palsu yang memicu perbandingan sosial negatif dan kecemasan.
Survei Kompas pada Februari 2025 mengungkap bahwa banyak anak Indonesia mengalami gangguan jiwa akibat bullying online atau ajakan bunuh diri yang viral.
Di Poltekkes Pangkal Pinang, studi Juli 2025, menemukan screentime berlebih memicu citra diri rendah dengan 45% remaja melaporkan gangguan tidur dan 40% penurunan produktivitas.
Jurnal ResearchGate Agustus 2025 bahkan menghubungkan media sosial dengan peningkatan kenakalan remaja, termasuk kekerasan digital yang naik signifikan sejak 2024.
Perbedaan dengan Australia terletak pada pendekatan. Di sana pemerintah bertindak preemptif dengan larangan didahului edukasi cyber safety dan penguatan undang-undang anti-bullying meski sempat menuai protes dari remaja yang khawatir isolasi.
Di Indonesia, respons masih reaktif. Ada regulasi seperti UU ITE, tapi implementasinya lemah.
Kementerian Kominfo pernah blokir konten negatif, tapi tanpa batas usia ketat seperti Australia.
Ini bukan soal melarang total, tapi mengelola new media sebagai alat komunikasi yang bertanggung jawab.
Australia membuktikan bahwa intervensi dini bisa menyelamatkan generasi. Di Indonesia, tragedi seperti kasus Tilly tak boleh direplikasi.
Bagaimana jika Indonesia mengadopsi model serupa? Batas usia 16 tahun untuk akun media sosial dikombinasikan kampanye nasional "Digital Sehat" yang edukatif.
Universitas Muhammadiyah Malang, melalui penelitian mahasiswanya pada Maret 2025, sudah menyoroti bagaimana perbandingan diri di media sosial memicu kecenderungan negatif.
Solusinya kurikulum sekolah yang integrasikan literasi digital plus kolaborasi dengan platform, seperti TikTok, untuk fitur parental control yang lebih ketat.
Di Jurnal Pendidikan Dasar Unpas Juni 2025, peneliti menekankan keseimbangan mental di era digital: Media sosial punya sisi positif seperti komunitas dukungan, tapi negatifnya perkembangan sosial terganggu jika tak terbiasa dengan teknologi secara bijak. Maka dari itu harus diimbangi regulasi.
Survei Jagat Review April 2025 menunjukkan 45% remaja mengakui dampak buruk pada tidur, tapi hanya sedikit yang punya tools untuk lepas.
New media bukan musuh, tapi senjata bermata dua yang butuh pedoman etis.
Australia memilih Christmas Unplugged atau libur Natal tanpa notifikasi untuk reset mental remaja.
Indonesia mungkin bisa mulai dengan "Hari Tanpa Scroll" nasional didukung influencer yang promosikan konten autentik, bukan filter sempurna.
Pemerintah harus lobi platform global untuk verifikasi usia yang ketat, sementara orang tua dilatih manajemen komunikasi digital.
Tanpa itu, kiamat media sosial bukan lagi isu Australia.
Cerita Emma Mason mengingatkan kita jika melindungi remaja bukan tentang mematikan lampu, tapi menyalakan cahaya alternatif dengan cara interaksi langsung dan percakapan terbuka.
Saat Australia memasuki era pembatasan media sosial untuk anak muda, Indonesia punya peluang belajar: Jangan biarkan algoritma mendikte masa depan generasi Z.
Waktunya bertindak sebelum terlambat. Karena di balik layar itu ada nyawa yang menunggu diselamatkan.




















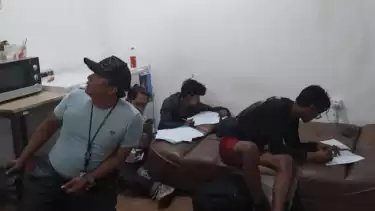




Load more